Sri Radjasa menyoroti bahwa hingga kini Aceh belum memiliki satu pun WPR yang ditetapkan secara resmi, meski payung hukumnya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba serta Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Padahal, data Dinas ESDM Aceh menunjukkan lebih dari 3.000 penambang rakyat masih beroperasi tanpa izin, dengan perkiraan cadangan emas mencapai lebih dari 20 ton. “Kita menghadapi situasi ironis, sumber daya besar dibiarkan tanpa tata kelola, sementara rakyat yang hidup dari situ justru dikriminalisasi karena ketiadaan payung hukum,” katanya.
Ia mendorong Pemerintah Aceh segera menyusun Qanun Pertambangan Rakyat Aceh sebagai solusi struktural untuk menata tambang rakyat. Menurutnya, qanun itu bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan hukum, lingkungan, dan kesejahteraan. “Qanun ini penting untuk melahirkan mekanisme legal yang memungkinkan rakyat tetap bekerja dengan aman dan ramah lingkungan. Tanpa itu, Aceh akan terus berputar dalam lingkaran tambang ilegal, penindakan, dan kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menilai keterlibatan organisasi Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) sangat penting karena lembaga tersebut telah berpengalaman dalam pendampingan teknis dan sosial di banyak daerah di Indonesia.
Sri Radjasa menilai rencana pembangunan laboratorium dan pusat pelatihan pengolahan emas ramah lingkungan yang pernah didiskusikannya dengan DPC APRI Aceh Selatan dapat dijadikan sebagai langkah progresif. Ia menilai fasilitas itu bisa menjadi pilot project bagi Aceh dalam membangun sistem tambang rakyat yang legal dan berkelanjutan. “Aceh Selatan misalkan, bisa dijadikan roll model untuk itu. Teknologi alternatif seperti leaching IDA dan sistem gravitasi terbukti lebih aman dan bebas merkuri. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Minamata yang menargetkan bebas merkuri pada 2025,” katanya.



























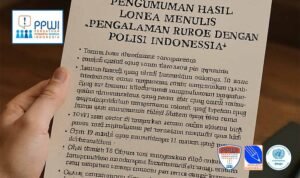




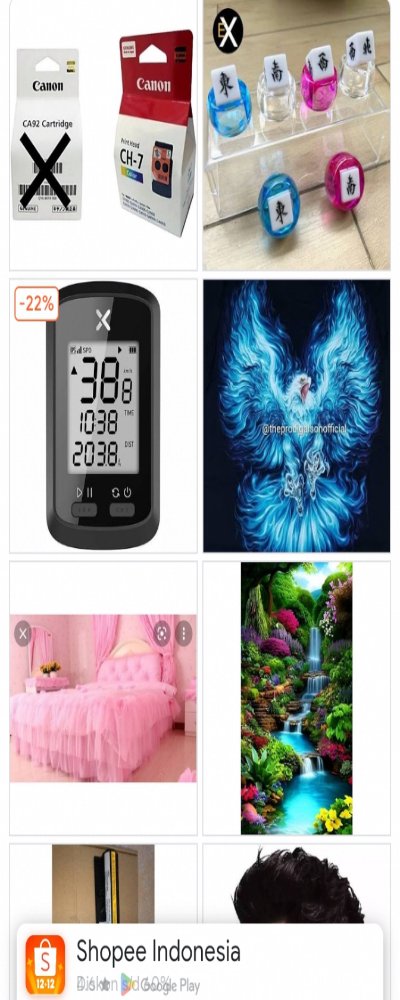





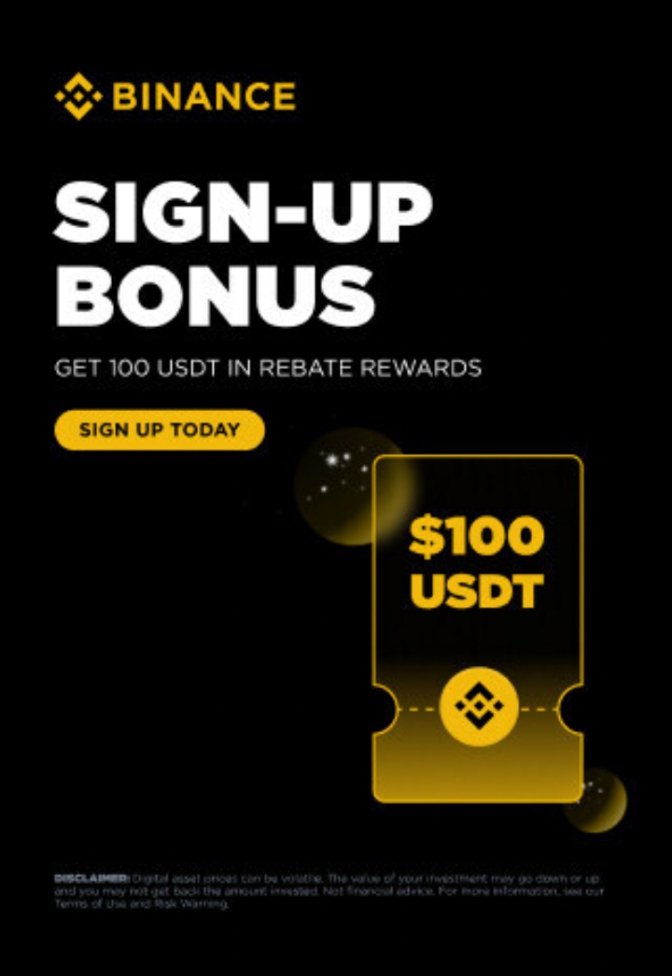





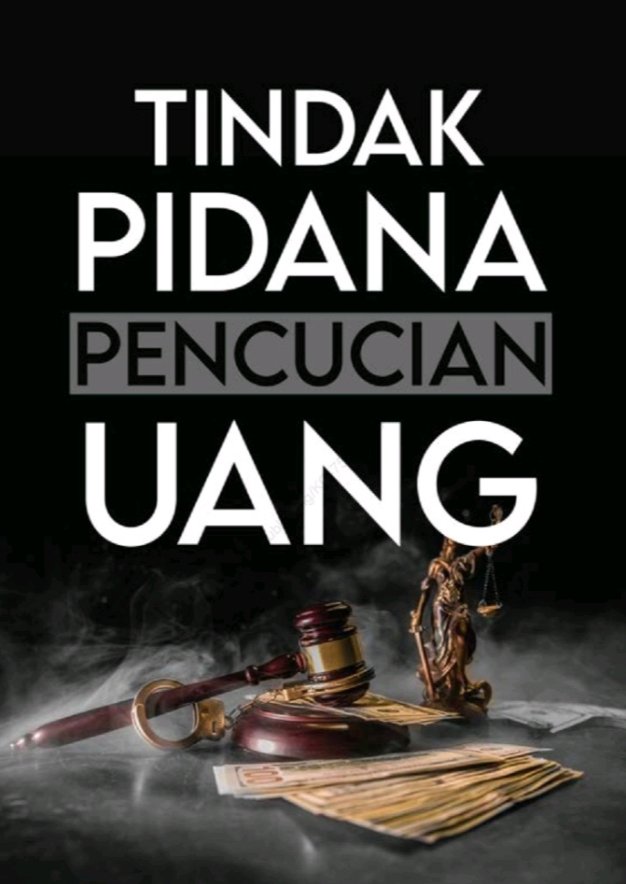







Komentar