Berdasarkan kekurangan prosedural dan substantif, gugatan dapat ditolak berdasarkan Pasal 132 HIR yang mengatur tentang gugatan rekonvensi atau gugatan balik oleh tergugat terhadap penggugat. Majelis Hakim juga dapat menolak gugatan berdasarkan Pasal 118 RBg yang mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri, yaitu kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu gugatan berdasarkan wilayah hukumnya, biasanya meliputi tempat tinggal tergugat, tempat penggugat jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, atau tempat benda tetap yang disengketakan.
Mengingat kekhawatiran publik dan potensi pelanggaran etika dalam proses hukum dan penyelesaian kasus ini, pengawasan oleh Komisi Yudisial sangat diperlukan. Kekhawatiran itu tidaklah berlebihan mengingat penggugat adalah oknum mafia tanah yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan backing aparat dan pejabat, baik di tingkat daerah maupun di pusat.
Majelis hakim yang menyidangkan kasus yang dikenal sebagai “Tipu-tipu Abunawas” ini dapat saja telah bertindak benar, mengambil keputusan yang sudah seharusnya dan adil, dengan memenangkan tergugat, namun pihak penggugat hampir dipastikan akan menggunakan jalur hukum yang tersedia untuk melakukan banding. Pada tahap ini, proses hukum yang penuh intrik dan manipulasi, kolusi dan korupsi suap-menyuap hakim akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemilik tanah dan publik. Demikian juga, jika kasus ini harus bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hal serupa juga sangat mungkin terjadi.
Kasus ini menggambarkan ketegangan antara formalisme hukum dan keadilan sosial. Lembaga peradilan harus bertindak tidak hanya sebagai penjaga prosedur tetapi juga sebagai penjaga keadilan. Jika dugaan-dugaan tersebut terbukti benar, gugatan ini merupakan upaya untuk menjadikan sistem hukum sebagai senjata untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, sebuah praktik licik yang harus ditolak dengan tegas.
Idealnya, pengadilan di negeri ini harus menegakkan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat setempat dan mencegah eksploitasi dan pencaplokan tanah rakyat melalui celah hukum. Pengadilan sebagai tempat mencari perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat semestinya berfungsi sebagai penjaga kehidupan masyarakat di mana kantor pengadilan itu berdomisili. Pengadilan harus diharamkan untuk dijadikan sebagai alat pemerkosa hak masyarakat yang telah turun-temurun tinggal di atas tanahnya oleh orang asing. (*)
Penulis: Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, lulusan pasca sarjana bidang studi Global Ethics dan Applied Ethics dari tiga universitas ternama di Eropa (Birmingham University, England; Utrecht University, The Netherlands; Linkoping University, Sweden)







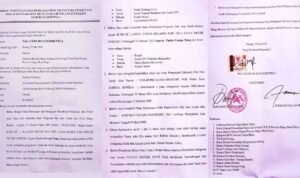




























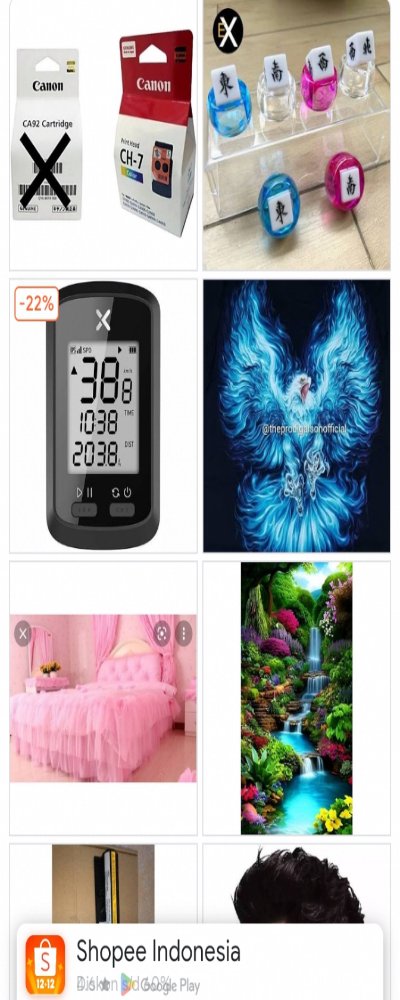






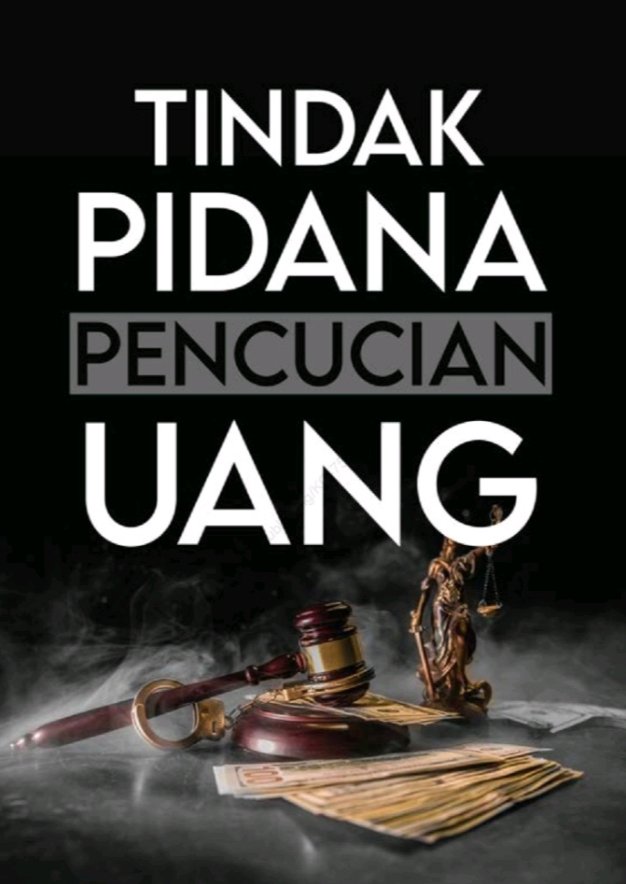






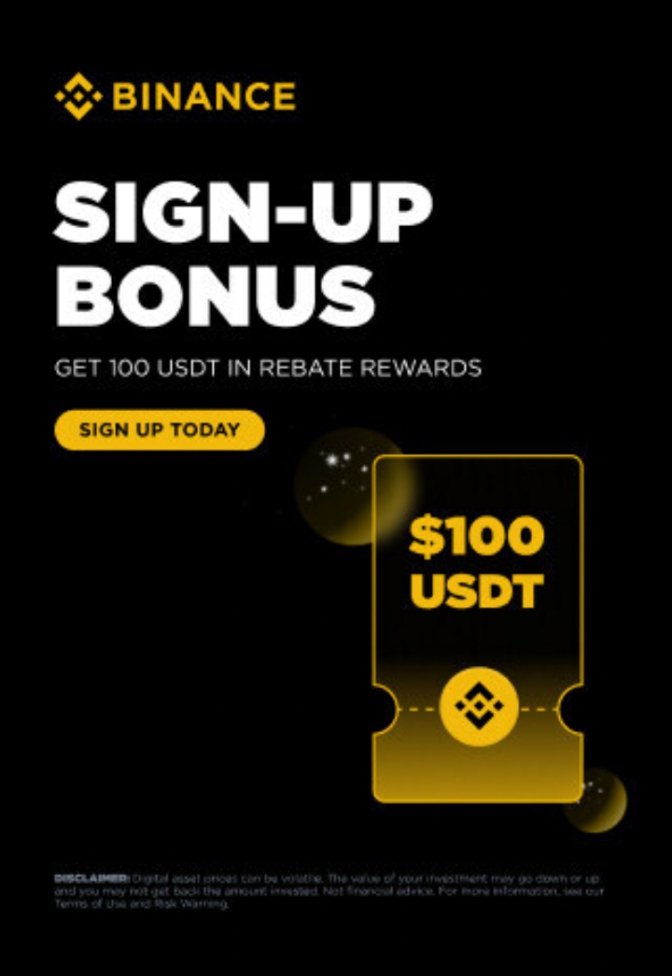

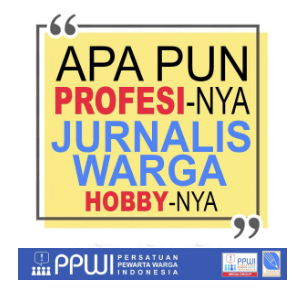




Komentar