ICJN – Sejak runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era desentralisasi politik yang diyakini sebagai cara meredam ketegangan pusat-daerah dan memberi ruang bagi daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Otonomi daerah menjadi titik balik setelah puluhan tahun kekuasaan terkonsentrasi di Jakarta. Namun setelah lebih dari dua dekade berjalan, desentralisasi ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan tata kelola yang kuat. Korupsi lokal meningkat, kebijakan daerah kerap berseberangan dengan kebijakan nasional, dan muncul figur-figur “raja kecil” yang menjadikan kekuasaan sebagai ladang patronase. Dalam konteks inilah kebijakan pemerintah Prabowo Subianto perlu dibaca bahwa resentralisasi yang muncul tidak lahir dari ruang kosong, tetapi sebagai respon atas kegagalan sebagian praktik otonomi di tingkat lokal.
Namun gejala penarikan kembali kewenangan ke pusat juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai arah konsolidasi kekuasaan. Pemangkasan Dana Alokasi Umum dan pengetatan ruang fiskal daerah, pengambilalihan penyelesaian sengketa batas wilayah, serta konsolidasi politik di tingkat nasional, memberi sinyal bahwa pemerintah pusat sedang memperkuat kontrol struktural. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan seragam dan strategis, terutama dalam proyek besar dan sektor pertambangan serta energi. Namun lembaga kajian seperti CSIS mengingatkan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan kemunculan gerakan separatis dan penolakan pusat seringkali bermula dari perasaan tersisih atau kehilangan kendali terhadap sumber daya di wilayah sendiri. Ketika daerah merasa diperlakukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, bukan mitra yang setara, maka luka kultural bisa tumbuh diam-diam.


































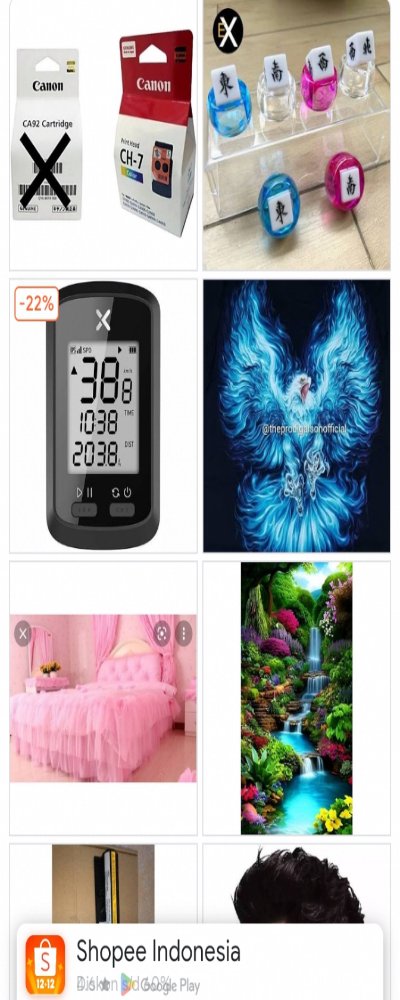











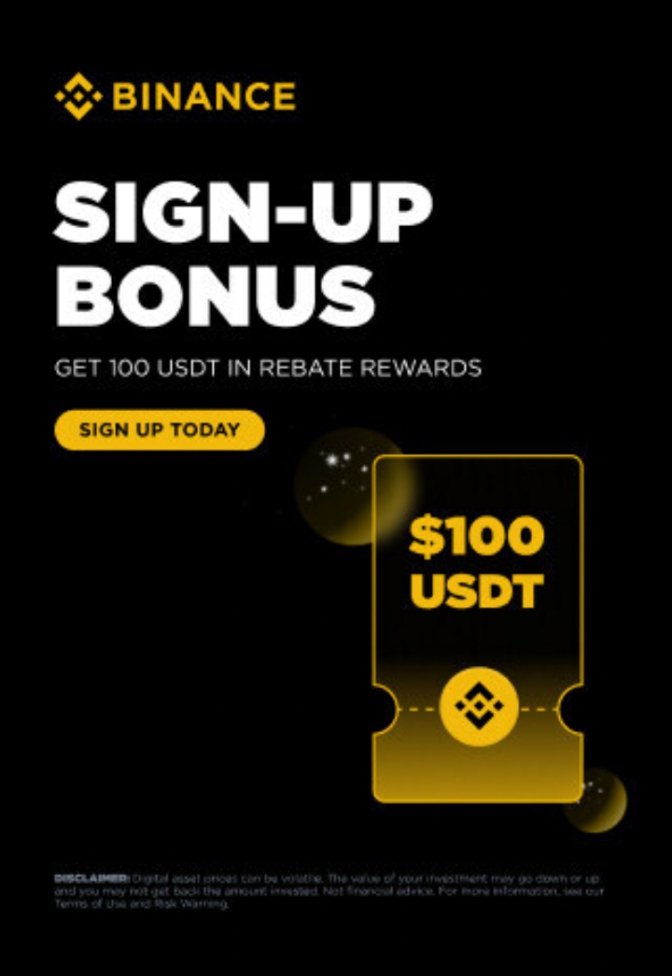

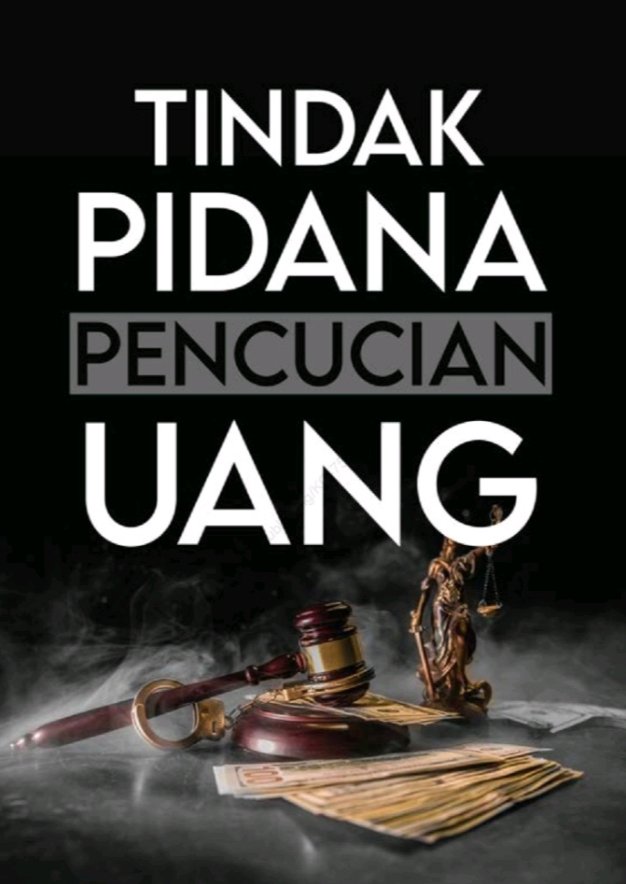

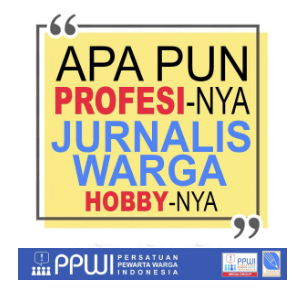




Komentar