Opini
Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
ICJN – Setelah dua dekade melewati masa damai, Aceh seolah sedang kembali mengulang sejarahnya sendiri. Jika dulu rakyat hidup dalam ketakutan karena konflik bersenjata, kini mereka hidup dalam kecemasan karena kekuasaan dan modal. Senjata memang sudah lama diam, tetapi bentuk penjajahan baru muncul dalam wajah yang berbeda yakni izin perusahaan tambang, surat rekomendasi, dan kolaborasi antara elit dan investor besar.
Persoalan tambang di Aceh ibarat kisah klasik yang terus berganti pemain, tetapi alurnya tak pernah berubah. Pejabat dan pengusaha besar datang membawa janji kesejahteraan, sementara rakyat kecil yang menjadi pemilik sah atas tanah dan alamnya hanya menjadi penonton dari cerita besar yang dimainkan atas nama pembangunan. Setelah lepas dari mulut buaya konflik, rakyat kini diterkam oleh mulut harimau ekonomi.
Kisah itu kini berulang di Aceh Selatan. Nama PT Empat Pilar Bumindo mencuat setelah disebut-sebut mengajukan permohonan rekomendasi ke sejumlah keuchik di Kecamatan Samadua untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Di permukaan, prosesnya tampak normatif, seolah mengikuti aturan yang berlaku. Namun di balik layar, kabar tentang dugaan intervensi pejabat lokal di kecamatan kepada Keuchik membuat rakyat resah dan kembali kehilangan kepercayaan pada kebijakan pemerintah yang dulu mereka harapkan berpihak kepada rakyat kecil.
Padahal, rakyat Aceh sempat menaruh harapan besar pada kepemimpinan Gubernur Mualem, yang di awal pemerintahannya tampil tegas menertibkan tambang ilegal. Tapi kini, arah kebijakan itu tampak kabur. Investor besar kembali masuk, membawa nama pejabat daerah dan pusat, bahkan disebut-sebut mencatut nama lingkaran presiden untuk melancarkan izin. Di sisi lain, ribuan penambang rakyat di Aceh Selatan masih bekerja dengan alat sederhana, tanpa perlindungan hukum, tanpa izin, dan tanpa kepastian.









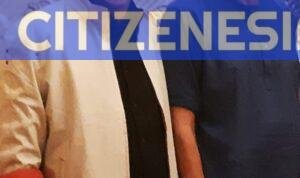
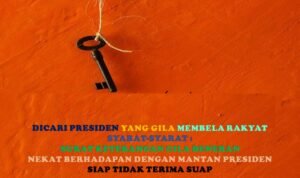




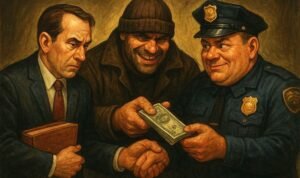

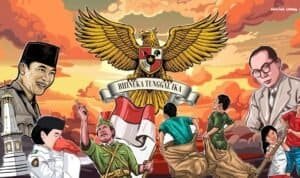


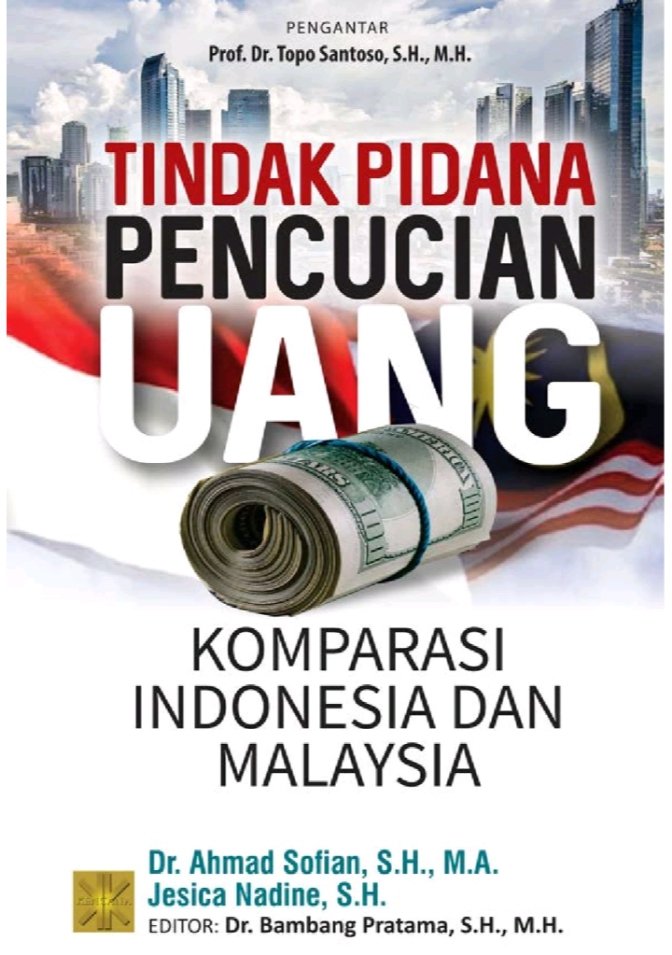






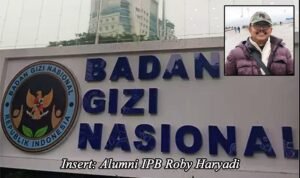




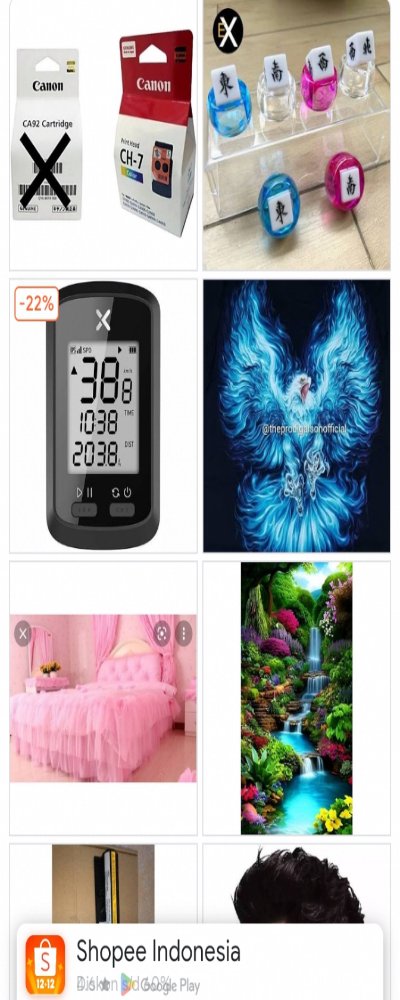

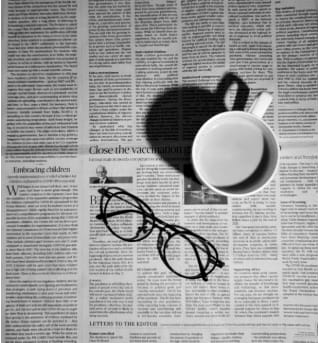



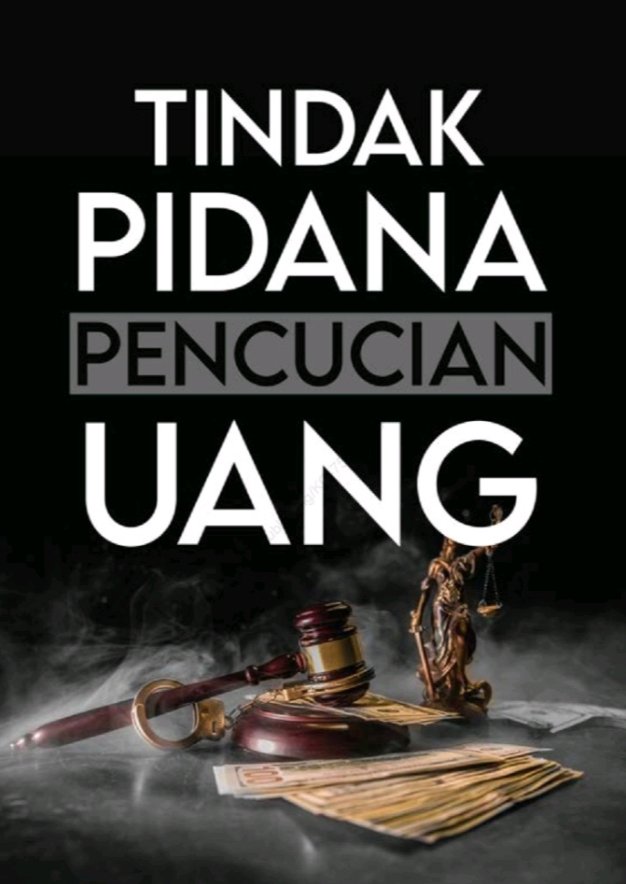


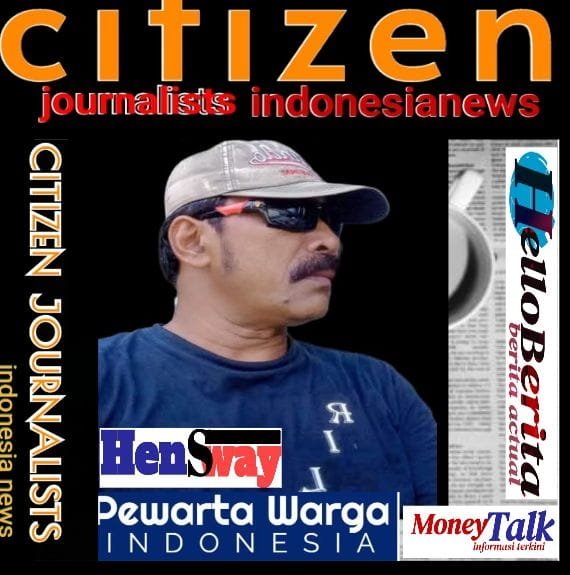

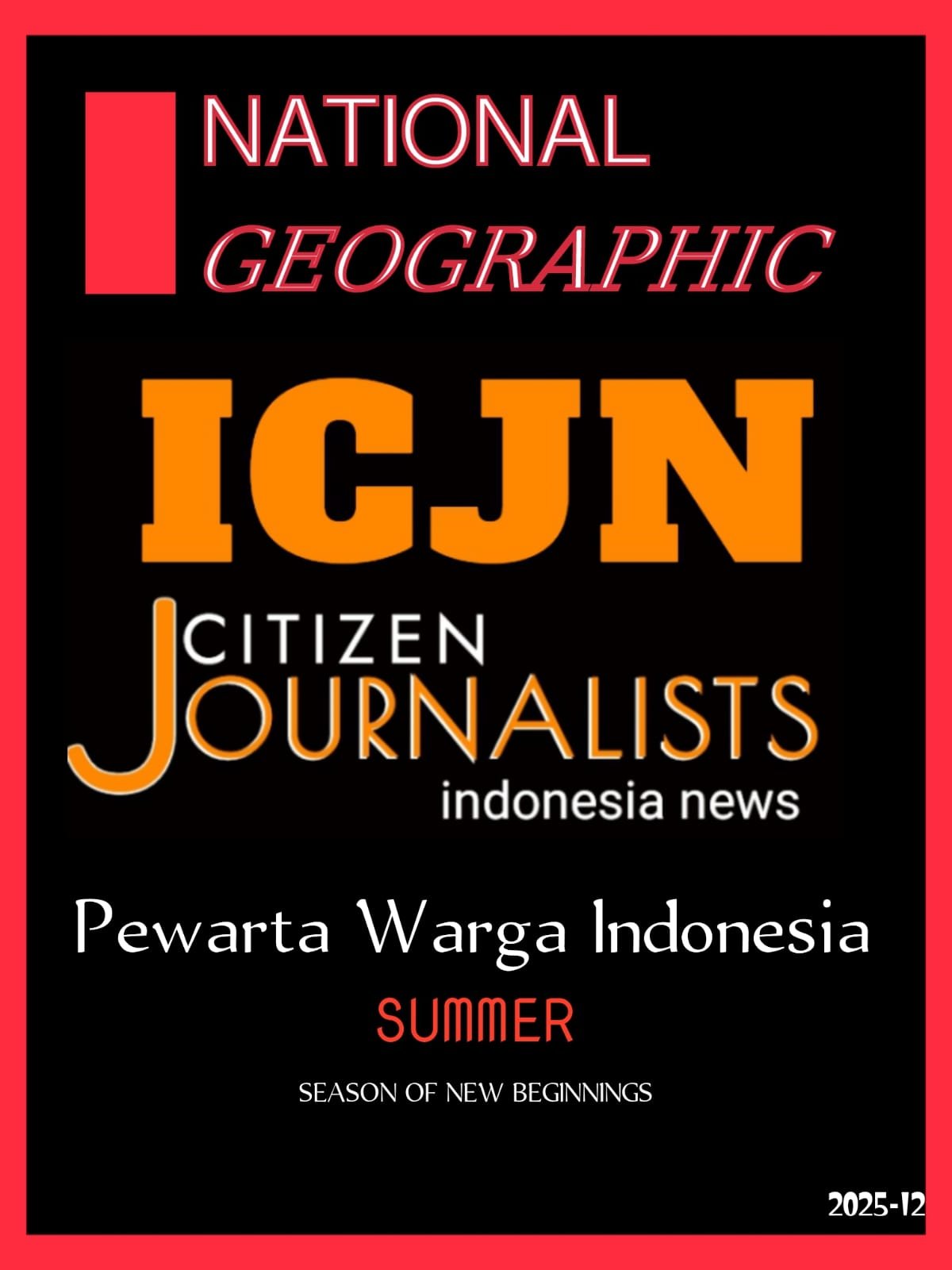
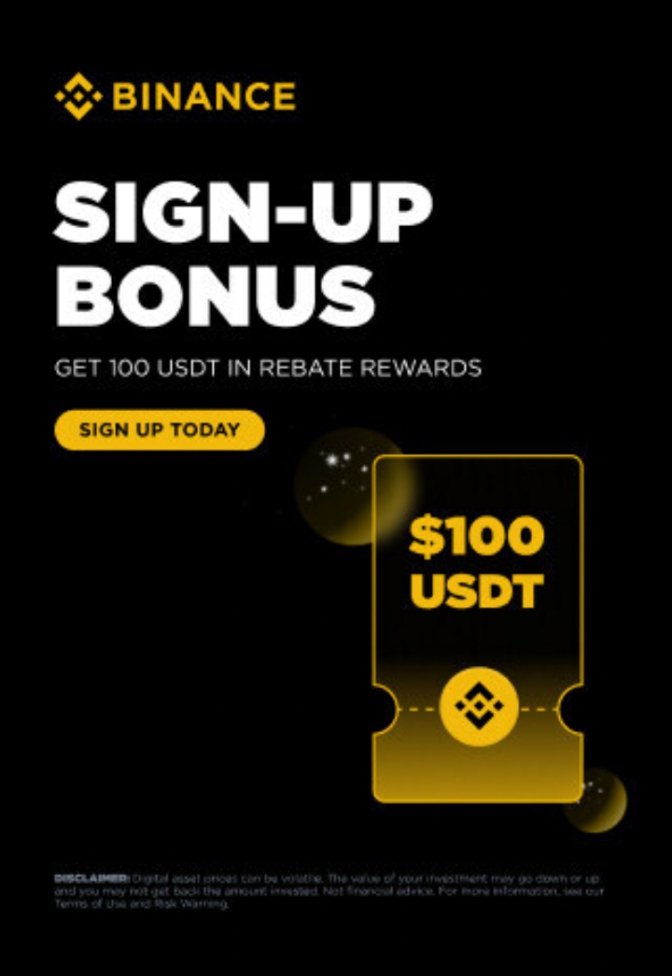



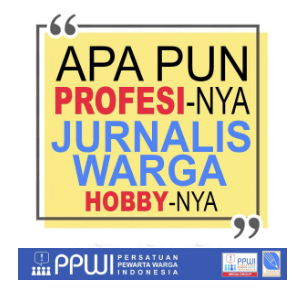



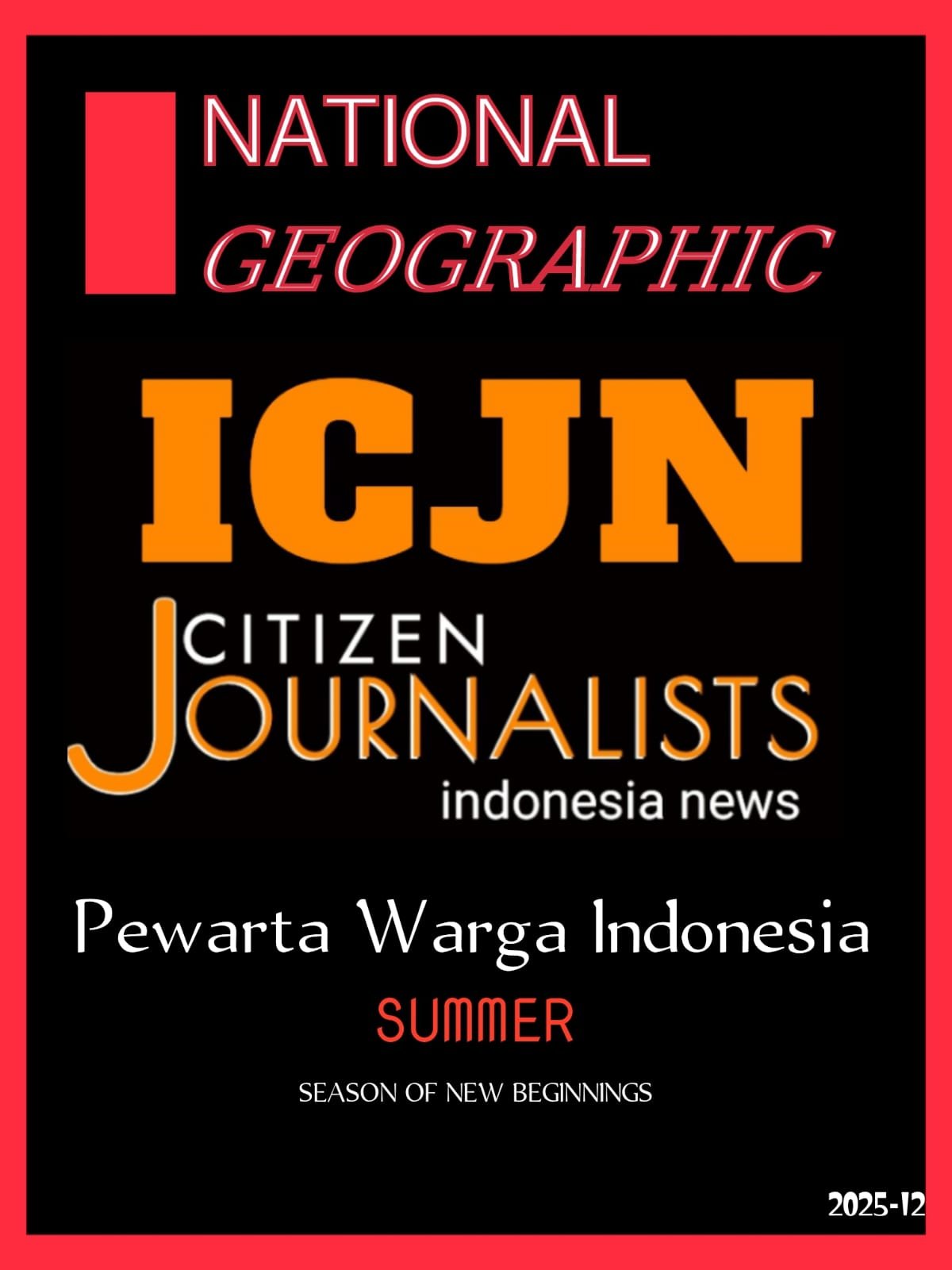
Komentar